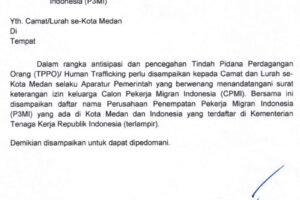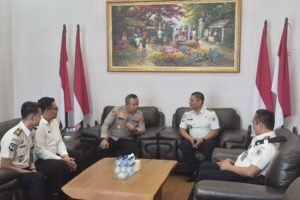Oleh: Ervina Sari Sipahutar, S.H., M.H.
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Sumatera Utara
Kamis, 23 Oktober 2025
Pendahuluan
Perencanaan pembangunan daerah merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas. Di era desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk menentukan arah pembangunan sesuai dengan potensi serta kebutuhan lokal masing-masing. Namun, di sisi lain, desentralisasi juga menghadirkan tantangan dalam hal keseragaman dan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan.
Oleh karena itu, standarisasi tata kelola menjadi kebutuhan mendesak agar proses perencanaan tidak hanya efektif, tetapi juga transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, peran sistem hukum sangat vital, karena sistem hukum yang dianut suatu negara secara fundamental memengaruhi mekanisme, instrumen, dan implementasi tata kelola pembangunan daerah. Dengan demikian, membandingkan bagaimana berbagai sistem hukum mengatur standarisasi tata kelola perencanaan pembangunan menjadi langkah penting untuk menemukan model terbaik yang sesuai dengan konteks nasional dan lokal.
Sistem Hukum dan Karakteristik Tata Kelola Pembangunan Daerah
Secara umum, dunia mengenal dua sistem hukum utama, yaitu sistem civil law dan sistem common law. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal pembentukan hukum, penerapan, serta interpretasi aturan.
Sistem civil law—yang banyak dianut oleh negara-negara Eropa kontinental, termasuk Indonesia—menitikberatkan pada hukum tertulis dan regulasi yang sistematis. Regulasi formal menjadi alat utama dalam mengatur tata kelola pembangunan daerah, mulai dari pembentukan kelembagaan, proses perencanaan, hingga mekanisme evaluasi.
Dalam konteks standarisasi, sistem ini memberikan kerangka kerja yang jelas, baku, dan mengikat sehingga setiap daerah wajib mengikuti prosedur yang seragam sesuai regulasi yang berlaku.
Namun, sistem civil law sering kali dikritik karena dianggap kurang adaptif terhadap dinamika sosial dan perubahan yang cepat. Ketergantungan yang tinggi pada aturan tertulis dapat menghambat fleksibilitas dalam merespons kebutuhan inovasi dan kebijakan yang mendesak. Akibatnya, proses perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi lambat dan kurang responsif terhadap perubahan di lapangan.
Berbeda dengan civil law, sistem common law—yang berkembang di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia—lebih mengedepankan prinsip preseden dan kebebasan interpretasi pengadilan. Dalam sistem ini, standarisasi tata kelola lebih banyak bergantung pada praktik hukum yang berkembang melalui putusan pengadilan dan praktik administrasi yang dinamis.
Fleksibilitas tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan menyesuaikan standar tata kelola dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Meski demikian, sistem ini juga menuntut kemampuan kelembagaan yang tinggi agar hukum dapat diterapkan secara konsisten. Kelemahan utamanya adalah potensi ketidakpastian hukum dan inkonsistensi standar antarwilayah, yang dapat mengganggu sinkronisasi pembangunan nasional.
Implikasi Perbandingan Sistem Hukum terhadap Standarisasi Tata Kelola
Perbandingan kedua sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan.
Sistem civil law unggul dalam memberikan kepastian hukum, regulasi yang jelas, serta prosedur yang terstruktur, sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Namun, kekakuan aturan formal dapat membatasi ruang inovasi di tingkat daerah.
Sebaliknya, sistem common law lebih adaptif dan inovatif, karena memberikan ruang interpretasi yang luas. Akan tetapi, tanpa regulasi tertulis yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif, standarisasi tata kelola berisiko mengalami fragmentasi dan inkonsistensi, yang justru dapat menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan.
Banyak negara kini mulai mengembangkan pendekatan hibrida, yaitu menggabungkan unsur-unsur civil law dan common law untuk mengoptimalkan tata kelola pembangunan daerah. Pendekatan ini mempertahankan regulasi tertulis yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, sembari memberikan ruang fleksibilitas dalam pelaksanaannya agar daerah dapat berinovasi sesuai karakteristik lokal. Dengan demikian, standarisasi tata kelola bukan hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan daya saing perencanaan pembangunan.
Studi Kasus: Indonesia dan Negara dengan Sistem Hukum Berbeda
Indonesia sebagai negara yang menganut civil law telah berupaya mewujudkan standarisasi tata kelola pembangunan daerah melalui berbagai regulasi, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Kedua regulasi tersebut memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai prosedur perencanaan, peran kelembagaan, serta mekanisme pengawasan. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan berupa disparitas kapasitas sumber daya manusia, perbedaan kualitas kelembagaan, dan kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sebagai perbandingan, negara dengan sistem common law seperti Amerika Serikat menerapkan standar tata kelola pembangunan daerah yang lebih fleksibel. Sistem ini sangat bergantung pada kekuatan lembaga pengadilan serta pengawasan internal pemerintahan daerah. Standar yang adaptif memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan lokal, namun memerlukan koordinasi yang intensif agar tetap selaras dengan kebijakan nasional. Model ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan transparansi publik sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial.
Tantangan dan Peluang
Tantangan utama dalam mewujudkan standarisasi tata kelola perencanaan pembangunan daerah adalah bagaimana menyeimbangkan antara kepastian hukum dan fleksibilitas inovasi lokal.
Dalam konteks desentralisasi, setiap daerah memiliki keragaman sosial, ekonomi, dan budaya yang menuntut pendekatan tata kelola yang tidak kaku, namun tetap berada dalam koridor hukum yang jelas.
Peluang dapat diperoleh melalui:
- Pengembangan regulasi yang adaptif,
- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antarlembaga.
Sistem hukum yang ideal adalah yang mampu menjembatani antara kontrol administratif dan kebebasan inovasi, dengan menyediakan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.
Kesimpulan
Perbandingan antara sistem civil law dan common law dalam konteks standarisasi tata kelola perencanaan pembangunan daerah memberikan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan dan akademisi. Tidak ada sistem yang sempurna; namun, pemahaman mendalam terhadap karakteristik dan implikasi masing-masing sistem dapat menjadi dasar dalam merancang kerangka hukum dan kelembagaan yang lebih efektif, responsif, dan inklusif.
Standarisasi tata kelola bukan sekadar persoalan teknis regulasi, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, budaya, dan politik yang melekat pada sistem hukum suatu negara. Oleh karena itu, reformasi tata kelola pembangunan daerah harus dirancang secara holistik dengan memperhatikan konteks hukum nasional dan dinamika lokal. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan secara terencana, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.